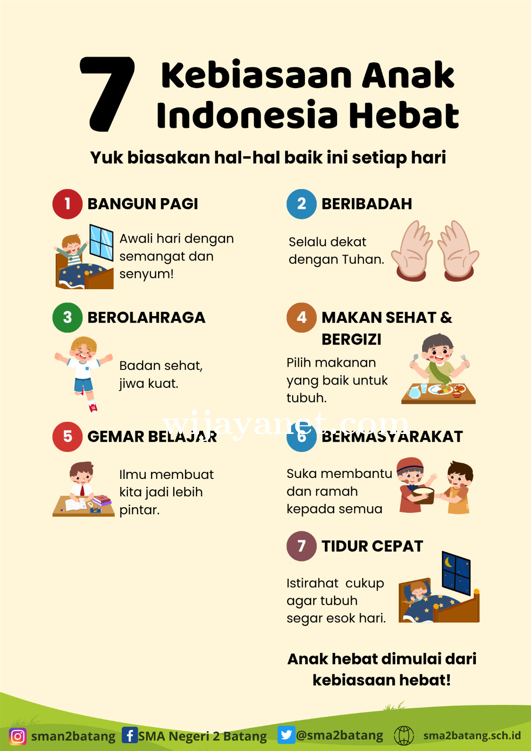Diseminasi Pembelajaran Mendalam
Pembelajaran Mendalam
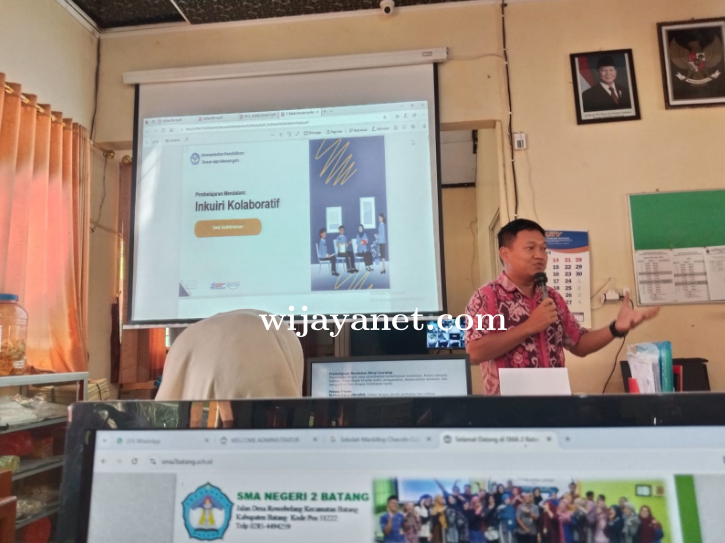
Pada hari ini Selasa tanggal 9 September 2025 di SMA Negeri 2 Batang dilaksanakan Diseminasi Pembelajaran Mendalam dengan narasumber 1. Bapak Sugeng, S.Pd., M.Pd.; 2. Nurhayin Fatkhulhasan, S.Pd; 3. Aqiilah, S.Pd; 4. Bagja Sumantri, S.Pd.
Apa itu Deep Learning?
Istilah Deep Learning yang dipakai oleh Mendikdasmen tidak sama dengan istilah Deep Learning yang lazim digunakan dalam ranah Artificial Intelligence (AI). Dalam konteks pendidikan, Deep Learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam dalam cakupan materi yang lebih sempit.
Dalam Deep Learning, siswa didorong untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan menyelami topik yang sedang dipelajari, sehingga ia dapat menjelajah lebih dalam dan menikmati keindahan panorama dari topik tersebut.
Pendekatan pembelajaran Deep Learning (belajar secara mendalam) adalah kontras dari pendekatan pembelajaran Surface Learning (belajar di permukaan) yang berusaha membahas banyak materi secara luas dengan mengorbankan proses pemahaman dan peningkatan kompetensi dari para peserta didik. Siswa akhirnya hanya terpaksa menghapal banyak hal tanpa dapat memaknai, memiliki, dan menikmati proses pembelajarannya.
Elemen Utama dalam Deep Learning
Menurut Mendikdasmen Abdul Mu’ti, pendekatan pembelajaran Deep Learning dapat tercapai melalui 3 elemen utama, yakni Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful Learning.
Melalui proses Meaningful Learning, siswa dapat memaknai hal-hal yang sedang ia pelajari. Kemudian, melalui proses Mindful Learning, siswa dapat menjadi agen aktif yang secara sadar berniat untuk mengembangkan pemahaman dan kompetensinya. Proses Joyful Learning membuat siswa menjadi termotivasi dalam menjalani proses pembelajarannya.
Mari kita bahas ketiga elemen ini secara lebih mendalam!
1. Meaningful Learning
Teori Meaningful Learning yang dicetuskan oleh David Ausubel menjelaskan proses pembelajaran dimana guru membantu siswa untuk mengaitkan konsep baru yang akan diajarkan dengan konsep-konsep yang sebelumnya sudah mereka pahami. Proses belajar Meaningful Learning ini bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa.
Misalnya, untuk memperkenalkan penjumlahan pecahan, kita bisa mulai dengan penjumlahan benda-benda yang lebih konkret terlebih dahulu.
1 ayam + 2 ayam = 3 ayam
1 bola + 2 bola = 3 bola
1 perlima + 2 perlima = 3 perlima → ? + ? = ?
Atau
1 ayam + 2 bebek = 1 unggas + 2 unggas = 3 unggas
1 lusin + 2 kodi = 12 buah + 40 buah = 52 buah
1 perdua + 2 pertiga = 3 perenam + 4 perenam = 7 perenam
2. Mindful Learning
Mindful Learning seringkali dikenal sebagai metakognisi dalam teori pendidikan. Dalam Mindful Learning, siswa diajak untuk senantiasa sadar akan proses pembelajaran yang sedang ia jalani. Kesadaran ini terdiri dari beberapa aspek:
- Kesadaran akan hal-hal yang sudah ia pahami atau kuasai sebelumnya,
- Kesadaran akan hal-hal yang belum ia pahami atau kuasai,
- Kesadaran akan pentingnya pemahaman atau penguasaan kompetensi dari apa yang ia sedang pelajari,
- Kesadaran akan alur proses pembelajaran yang sedang ia jalani demi tercapainya pemahaman atau kompetensi yang ingin ia capai,
- Kesadaran akan kemajuan pemahaman atau kompetensi setelah merefleksikan proses pembelajaran yang telah ia lewati,
- Kesadaran akan hal-hal yang masih dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam proses pembelajaran berikutnya.
Dengan demikian, siswa dituntun untuk menjadi agen aktif yang bertanggung jawab atas proses pembelajarannya sendiri.
Berbeda dengan orang dewasa, kesadaran ini bukanlah sesuatu yang dapat timbul secara otomatis dalam diri anak-anak, sehingga guru harus terus-menerus menghidupkan kesadaran ini dari awal sampai akhir proses pembelajaran.
Misalnya, guru bisa membiasakan siswa untuk selalu membuat kesimpulan pembelajaran sendiri di akhir sesi ajar dan merefleksikan perkembangan pemahaman atau kompetensinya. Melalui proses refleksi ini, siswa dapat memahami kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing, serta memiliki target yang lebih jelas untuk pembelajaran berikutnya.
3. Joyful Learning
Joyful Learning menekankan pentingnya menciptakan suasana belajar yang positif agar siswa dapat menikmati setiap bagian dari proses pembelajaran.
Contohnya, pendekatan pembelajaran melalui permainan (game) atau aktivitas interaktif dapat membuat siswa lebih antusias dalam belajar.
Hal ini penting untuk mendorong anak-anak agar lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan menikmati pengalaman belajarnya. Terlebih lagi jika dipadukan dengan aspek meaningful dan mindful learning, kita berharap siswa dapat memiliki motivasi intrinsik dalam belajar dan akhirnya menjadi pembelajar sepanjang hayat.




 Inquiry Collaboratif
Inquiry Collaboratif
Inkuiri kolaboratif lahir dari kesadaran bahwa pembelajaran terbaik terjadi ketika orang dewasa—termasuk guru—berani mempertanyakan praktiknya sendiri, terbuka terhadap masukan, dan bersedia membangun pengetahuan secara bersama. Ia menggabungkan kekuatan data, diskusi, dan aksi nyata di dalam kelas untuk menjawab satu pertanyaan mendasar: bagaimana kita dapat meningkatkan hasil belajar murid secara nyata? Berbeda dari refleksi individu yang kerap bersifat internal dan tidak terdokumentasi, atau diskusi informal di ruang guru yang seringkali hanya menjadi tempat berbagi keluh kesah, inkuiri kolaboratif bersifat terstruktur, berbasis bukti, dan diarahkan pada perubahan praksis yang konkret. Ini adalah upaya sistematis untuk terus memperbaiki praktik pembelajaran berdasarkan pengamatan nyata di kelas dan dialog antarprofesional.
Tujuan utama dari inkuiri kolaboratif bukan sekadar menghasilkan laporan, tetapi mendorong perubahan positif yang berdampak pada kualitas pengajaran dan hasil belajar murid. Dalam prosesnya, guru-guru bekerja dalam tim kecil untuk menggali tantangan pembelajaran, merancang solusi bersama, dan melaksanakan perbaikan secara iteratif. Proses ini memberikan ruang untuk berkembang, berbagi keahlian, dan yang paling penting—mendengarkan satu sama lain secara setara. Di dalam ruang inkuiri, tidak ada guru yang dianggap lebih tahu atau lebih hebat. Semua berangkat dari titik yang sama: keinginan tulus untuk belajar dan memperbaiki diri demi murid-murid mereka.
Agar inkuiri kolaboratif dapat berjalan dengan efektif, terdapat sejumlah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Pertama dan paling utama, ia harus berbasis data dan bukti nyata dari praktik pembelajaran. Tanpa landasan ini, diskusi mudah terjebak pada asumsi atau opini yang tidak akurat. Data bisa berasal dari hasil asesmen murid, observasi kelas, rekaman diskusi, atau bahkan refleksi tertulis dari murid sendiri. Kedua, kolaborasi dalam inkuiri tidak boleh bersifat hierarkis. Setiap anggota tim harus merasa dihargai, didengarkan, dan punya ruang untuk menyampaikan pendapat. Ketiga, budaya profesional yang terbuka dan reflektif menjadi fondasi penting. Guru harus mau menunjukkan keraguan, mengakui keterbatasan, dan membuka diri terhadap perubahan.
Prinsip berikutnya adalah struktur yang jelas namun tetap fleksibel. Inkuiri kolaboratif memiliki siklus kerja yang terarah, tetapi tetap memungkinkan improvisasi sesuai konteks sekolah. Fokusnya harus selalu kembali pada pembelajaran murid dan dampaknya. Bukan sekadar merancang program baru, tetapi benar-benar melihat bagaimana murid mengalami perubahan. Terakhir, inkuiri harus menjadi bagian dari pembelajaran profesional berkelanjutan di tempat kerja. Ia bukan program sesaat, tetapi budaya yang ditanamkan dalam rutinitas sekolah. Yang tidak kalah penting, seluruh proses harus kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan murid yang terus berkembang.
Dibalik prinsip-prinsip tersebut, inkuiri kolaboratif dibangun di atas nilai-nilai luhur yang menjadi ruh dari praktik pendidikan yang bermartabat. Kepercayaan menjadi dasar utama: kepercayaan antar guru, antara guru dan pimpinan sekolah, dan antara guru dan murid. Tanpa rasa aman, kolaborasi akan terasa penuh tekanan. Rasa hormat dan saling memuliakan memperkuat relasi kerja: tidak ada ide yang diremehkan, tidak ada kegagalan yang ditertawakan. Keterbukaan dan kejujuran menjadi tali yang mengikat proses belajar bersama. Guru-guru belajar untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mengemukakan pandangan dengan jujur, dan menanggapi masukan tanpa defensif. Di atas semuanya, komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan mendorong inkuiri untuk tidak berhenti di satu siklus. Ini adalah proses yang terus-menerus, seperti kehidupan itu sendiri. Kesetaraan dan keterlibatan semua pihak menjadi syarat mutlak—baik guru senior maupun guru baru, semua punya peran dan suara.
Inkuiri kolaboratif berjalan melalui empat tahap utama yang membentuk sebuah siklus reflektif: Assess, Design, Implement, dan Measure-Reflect-Change. Tahap pertama, Assess, dimulai dengan mengidentifikasi persoalan nyata dalam pembelajaran. Guru bersama timnya menggali data tentang karakteristik murid, tantangan di kelas, dan hasil belajar yang belum optimal. Dari sini, mereka menentukan fokus inkuiri yang spesifik, relevan, dan berdampak. Selanjutnya, pada tahap Design, tim merancang strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Strategi ini harus berkesadaran—didesain dengan memahami konteks murid; bermakna—terhubung dengan kehidupan nyata; dan membahagiakan—memberi ruang bagi murid untuk belajar dengan rasa ingin tahu dan percaya diri. Indikator keberhasilan pun dirumuskan secara konkret dan dapat diukur.
Tahap ketiga adalah Implement, di mana rancangan dijalankan di kelas dengan keterlibatan aktif dari guru dan murid. Dalam banyak praktik, sesi pembelajaran yang dirancang akan diamati oleh anggota tim lain melalui open class atau video rekaman. Tujuannya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami bagaimana strategi tersebut bekerja dalam situasi nyata. Observasi dan monitoring dilakukan dengan instrumen yang telah disepakati bersama, dan hasilnya menjadi bahan refleksi kolektif. Tahap terakhir adalah Measure, Reflect, and Change. Di sini, guru mengukur dampak dari intervensi yang dilakukan, lalu duduk bersama tim untuk merefleksikan hasilnya. Apa yang berhasil? Apa yang masih menjadi tantangan? Apa yang bisa diperbaiki di siklus berikutnya? Dari sinilah tercipta perubahan praksis yang konkret dan berkelanjutan.
Agar proses ini berjalan secara produktif, beberapa strategi penerapan dapat digunakan. Membangun dialog terbuka dan reflektif adalah langkah awal yang penting. Guru perlu difasilitasi untuk bisa berdiskusi tanpa rasa takut atau malu. Refleksi berbasis data menjadi alat untuk membumikan diskusi, agar tetap fokus pada tujuan. Panduan diskusi yang sistematis membantu tim inkuiri agar tidak melebar ke mana-mana, tetapi tetap berada pada alur yang konstruktif. Yang tak kalah penting adalah penggunaan bahasa yang membangun: tidak menyalahkan, tidak menggurui, tetapi menanyakan, menanggapi, dan memberi umpan balik secara empatik. Di sinilah keterampilan komunikasi menjadi bagian integral dari kerja kolaboratif.